Mashlahah Mursalah
Dalam Urgensinya Sebagai Teori Hukum
(Perspektif Kajian Hukum Bisnis)
Teori Maslahat ini urgen sekali dipergunakan sebagai teori kajian dalam hukum bisnis khususnya dalam hukum perbankan syari’ah. Alasan digunakannya teori Maslahat dalam kajian hukum bisnis ini adalah terletak pada subtansi bahasannya; di mana secara filosofis hukum perbankan syari'ah sesungguhnya berasal dari hukum Islam. Karakteristik yang paling fundamental dalam kajian hukum yang berasal dari agama adalah sulitnya didekati dengan pemikiran manusia. Pasalnya adalah permasalahan agama adalah permasalahan keyakinan. Sedangkan keyakinan sulit sekali didekati dengan model (teori) hasil pemikiran manusia. Satu-satunya cara yang paling dianggap mudah dan relevan adalah teori yang berasal dari agama (keyakinan) itu sendiri. Itulah sebabnya teori Maslahat digunakan sebagai grand theory dalam kajian-kajian hukum bisnis syari’ah semisal hukum perbankan syari’ah.
A. Pengertian Teori Maslahat
"Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya"[1], merupakan kata-kata bijak yang sangat berarti dalam kehidupan umat manusia. Ungkapan ini sekalipun singkat dan sederhana, akan tetapi memiliki keluasan makna yang sangat dalam dan berarti[2]. Ungkapan tersebut setidaknya dapat dimaknai bahwasanya kehadiran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus dapat memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupannya. Nilai positif tersebut dapat ditafsirkan setidaknya sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang diharapkan dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Jeremy Bentham seorang sarjana berkebangsaan Inggris lebih menitikberatkan tujuan hukum pada nilai kemanfaatannya. Sehingga dengan demikian hukum diharapkan mampu memberi kemanfaatan sebanyak-banyaknya kepada orang. Hanya saja unsur kemanfaatan di sini masih bersifat umum. Persoalan yang muncul berikutnya adalah: apakah sesuatu yang berfaedah bagi seseorang juga berfaedah bagi orang lain atau bahkan merugikan orang lain dan umum.[3] Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan keumuman unsur manfaat di sini adalah apabila hukum itu dapat memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan orang sebanyak-banyaknya. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan dinilai baik atau buruk berdasarkan ukuran dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.[4] Berkaitan dengan hal ini Bentham berpendapat bahwa: kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (the greatest happiness of the greatest number). Berkenaan dengan dapatnya hukum memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya orang, hukum juga diharapkan dapat memberikan nilai keadilan. Sehingga dengan demikin secara subtansial hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu asas keadilan dan faedah atau kemanfaatan.[5] Teori Kemanfaatan (utilitis) ini secara umum sangat tepat dan berguna dalam pembahasan yang berkaitan dengan perekonomian. Hanya saja dalam kajian yang bekaitan dengan perbankan syari'ah, teori kemanfaatan (utilitis) nampaknya masih mengandung banyak kelemahan. Setidaknya kelemahan tersebut terletak pada dua hal. Pertama, sesuatu dapat dikatakan manfaat tetapi belum tentu maslahat. Karena nilai manfaat itu sering-kali hanya diukur dari kesenangan sepihak dan bersifat sementara. Kesenangan bagi seseorang, belum tentu berarti kesenangan bagi orang lain. Bahkan terkadang bisa merupakan penderitaan baginya. Contoh dari hal ini adalah: pengambilan keuntungan melalui jalan riba. Bagi pihak yang beruntung, riba memang dapat dikatakan manfaat, karena dapat mendatangkan kesenangan. Tetapi bagi pihak lain (yang diambil keuntungannya) sesungguhnya merupakan penderitaan yang tidak disadari. Kedua, terletak pada obyek kajiannya. Perbankan syari'ah yang dijadikan obyek kajian di sini, secara epistemologi berasal dari sistem ekonomi (agama) Islam. Sedangkan agama merupakan produk ketuhanan yang bersifat absolut. Karena sifat keabsolutannya itulah pada umumnya agama sulit sekali dipengaruhi oleh hasil-hasil pemikiran manusia . Berbeda dengan hukum umum sebagaimana adanya adalah merupakan produk manusia yang bersifat nisbi atau relatif. Sekalipun demikian teori kemanfaatan (utilitis) di sini, diidentikkan dengan teori maslahat (perspektif Hukum Islam). Karena teori Maslahat dalam kerjanya selalu berpijak pada nilai manfaat terlebih dahulu.
Teori maslahat ini berasal dari teori hukum Islam yang orientasi bidikannya lebih menekankan kepada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat al-Qur’an dan al-Hadits) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai, yang terkandung di dalam nas atau teks tersebut (Maqashid syariah}. Oleh karenanya terkadang teori maslahat ini secara lahiriah nampak tidak sejalan dengan teks undang-undang baik berupa ayat al-Qur’an maupun al-Hadits, akan tetapi kalau dicermati sesungguhnya justru mengembangkan dan membawa prinsip-prinsip dan misi hukum yang terkandung di dalam teks tersebut[6]. Najm al-Din al Thufy, dalam hal ini berpendapat lebih ekstrim lagi. Ia lebih mengedepankan maslahat dari pada nas (teks al-Qur’an dan al-Hadits) dalam hal muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, seperti bisnis dan lain sebagainya).[7] Hanya saja pendapat Najm al-Thufy ini kemudian dikomentari oleh sebagian pakar hukum, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah manakala maslahat tersebut dihadapkan dengan nas yang dhanny[8]. Adapun nas yang qoth’y[9] menurutnya nas harus tetap didahulukan, dalam arti maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas[10]. Itulah sebabnya, dalam pembaruan pemikiran hukum Islam, Syaltut juga menggunakan metode maslahat, bahkan dalam kasus tertentu ia lebih mendahulukan maslahat dari pada nas[11] sebagaimana pernyataan al-Thufy.
Teori maslahat ini dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan sedikit perbedaan, akan tetapi keseluruhannya mengarah pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya adalah: Imam Al-Ghazali (w. 505 H) dengan bukunya yang berjudul “Al-Mustasyfa”, Imam Syatibi dengan bukunya yang berjudul “Al-Muwafaqat”, Imam Najm al-Din al-Thufy (W. 716 H) dengan bukunya yang berjudul “Al-Ta’yin fi Syarh al Arba’in, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang bersifat komplementer dalam pembahasan teori maslahat ini.
Adapun pengertian maslahat ditinjau dari segi etimologis berasal dari kata bahasa Arab al-mashlahah (المصلحة ) dari kata kerja shalaha-yashluhu (صلح - يصلح ) yang berarti kebaikan. Kata al-mashlahah adalah bentuk tunggal (mufrad), sedangkan jamaknya adalah al-mashaalih (المصالح ) mengikuti wazan (timbangan kata) al-mafaa’il ) المفاعل) yang menunjukkan arti sesuatu yang banyak. Oleh karena itu kata maslahat berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam, pengertian maslahat dinegasikan dengan “mafsadat (Al- mafsadah) sesuatu yang membawa madarah (madarat, bahaya, bencana, atau kerusakan) atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Menurut istilah keagamaan, berati lawan makna maslahat”[12].
Berdasarkan pengertian etimologis di atas, maslahat memiliki dua pengertian. Pertama; hakiki, yaitu maslahat sama dengan manfaat[13], baik dari segi lafal maupun maknanya. Kedua; majazi (metaforis), yaitu maslahat berarti suatu pekerjaan yang mengandung shalah (kebaikan) yang berarti manfaat. Apabila dikatakan perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[14] Terkadang yang menjadi sebab kemaslahatan itu adalah mafsadat atau kerusakan, karena itu diperintahkan atau dibolehkan mengerjakannya. Hal itu bukan karena ia merupakan mafsadat atau kerusakan, tetapi karena ia mengantarkan kepada kemaslahatan.[15]
Mencermati berbagai pendapat tentang pengertian maslahat di atas dapat disimpulkan, bahwasanya secara etimologis, kata maslahat menunjuk kepada pengertian manfaat yang hendak diwujudkan oleh manusia. Penunjukan makna tersebut dimaksudkan untuk meraih kebajikan atau hal yang lebih baik dalam kehidupan umat manusia dikemudian hari, yang dalam kenyataannya selalu berkembang seirama dengan berkembangnya peradaban dan kebudayaan umat manusia. Sementara itu al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam hanya menjelaskan segala aspek kehidupan ini secara garis besar atau global. ”Teks-teks al-Qur’an dan al-Hadits sebagai nas hukum itu terbatas (ijaz), sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi tidak terbatas, oleh karena itu diperlukan ijtihad untuk menginterpretasi nas yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nas dapat dicari pemecahannya[16]. Oleh karena itu persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas secara konfrontatif, tapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi[17]. Wawasan semacam ini memang merupakan anjuran bahkan perintah para pakar hukum Islam dari generasi ke generasi guna menggali dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum. Anjuran tersebut secara monomental banyak dihafal oleh generasi sekarang dari berbagai elemen atau sekte dalam Islam sebagai slogan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Bunyi slogan tersebut adalah: المحافظة بالقديم الصالح و الأحذ من الجديد الأصلح {Al- muhafadhah bi al-qadim al-shalih wa al-ahdzu min al-jadid al-ashlah. ("Menjaga hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik")}. Bahkan tidak hanya mengambil yang lebih baik melainkan menciptakan yang lebih baik, sebagai nalar progresif demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pembinaan dan pembangunan hukum. Khususnya yang terkait dengan kajian ini adalah hukum perbankan syari'ah. Pemikiran semacam ini difasilitasi oleh Q.S. Al-Rahman ayat: 33
"Ya ma’syara al-jinni wa al-insi in istatha’tum an tanfuzu min aqthari al-samawati wa al-ardli fanfuzu wa la tanfuzuna illa bisulthan"[18]
Artinya:
“Wahai para jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan”.
Kekuatan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dari tinjauan terminologis, maslahat memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan pendapat masing-masing pakarnya. Al-Imam al-Ghazali (W. 505 H.) dalam kitabnya al-Mustasyfa mengemukakan pendapatnya bahwa maslahat pada dasarnya adalah suatu gambaran dari mendatangkan manfaat (jalb al-manafi’) atau menghindarkan kerusakan atau bahaya (daf’ul mafasid). Lebih lanjut al-Ghazali menegaskan: “Al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ (al-muhafadhah li al maqashid al syar’iyyah). Al-Mashlahah adalah meraih manfaat dan menghindarkan bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara’ yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta” [19].
Definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali tersebut sesungguhnya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu dapat dikatakan maslahat apabila memenuhi dua syarat, di mana syarat yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pertama; bernilai atau tidaknya sesuatu itu tergantung kepada nilai maslahat dan manfaatnya terhadap kehidupan umat manusia dalam menjaga tujuan syara’ yang lima yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kedua; adanya kesesuaian (relevansi) kemanfaatan tersebut dengan syara’(sumber hkum Islam). Kedua syarat ini kemudian direkomendasikan sebagai alat perubahan dan pengembangan ilmu hukum (Islam) untuk menjawab tantangan perubahan sosial di bidang hukum. Segala kepentingan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif, mendapatkan legitimasi maslahat, selama dapat mengakomodir kedua syarat tersebut. Oleh karena itu segala kepentingan yang didasarkan pada pemikiran akal dan hawa nafsu belaka, pasti akan ditolak. Di sini teori maslahat memberikan peluang seluas-luasnya kepada segala upaya pengembangan dan pembangunan hukum, termasuk upaya politik, selama tidak bertentangan dengan maslahat yang dimaksudkan.
Bertitik tolak dari pengertian maslahat yang dikemukakan Al-Ghazali tersebut, maka argumentasi apapun yang dikemukakan oleh seseorang dengan mengatasnamakan kepentingan, manakala bertentangan dengan dalil syara’ (hukum Islam), ia akan ditolak dan tidak dapat disebut sebagai maslahat, bahkan disebut sebagai mafsadat atau kerusakan. Jelasnya, segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan tujuan syara’ yang lima ia berhak dinamakan maslahat akan tetapi kalau mengabaikan tujuan syara’ yang lima tersebut berhak dinamakan mafsadat. Bahkan menolak sesuatu yang mengabaikan tujuan syara’ (yang lima) tersebut justru merupakan suatu maslahat.[20] Dilain pihak, Al-Khawarismi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al Zuhaily[21] menyatakan bahwa al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia
Kedua definisi di atas di samping memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Definisi maslahat oleh Al-Khawaritsmi sekupnya lebih sempit bila dibandingkan dengan definisi oleh Imam Al-Ghazali. Al-Khawaritsmi hanya memandang maslahat dari sisi menghindar dari kerusakan saja. Sementara Al-Ghazali, disamping dari sisi kerusakan juga dari sisi manfaatnya. Oleh karena itu hasil pandangan dari kedua pakar tersebut jelas menunjukkan adanya perbedaan sekaligus menunjukkan kesamaan di sisi yang lain. Hal tersebut karena ketika orang menghindar dari mafsadat atau kerusakan, belum tentu ia mendapatkan manfaat, kecuali hanya manfaat terhindar dari kerusakan yang dimaksud. Sedangkan manfaat secara material (partikular) tidak didapatkannya. Berbeda bila memakai optik definisi al-Ghazali, selain manfaat terhindar dari kerusakan juga mendapatkan manfaat secara material dari obyek hukum yang dimaksudkan.
Berkaitan dengan tradisi, Najm al-Din al-Thufi (W. 716) menjelaskan bahwa maslahat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan menurut syara’ maslahat adalah sesuatu yang menjadi sebab mendatangkan kepada tujuan pembuat hukum (al-Syari’) baik secara ibadah maupun adat kebiasaan”. [22] Pada dasarnya definisi yang disampaikan oleh Al-Thufi tersebut tidaklah jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Al-Ghazali, perbedaannya hanya terdapat pada formasi antara meraih kemanfaatan (jalb al-manafi’) yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dengan rumusan "sebab yang mendatangkan/melahirkan kebaikan dan kemanfaatan" (al-Sabab al-maaddi ala al-shalah wa al-naf’i) oleh Al-Thufi. Demikian juga dengan rumusan yang kedua, secara syar’i (islamic law), yakni yang menghubungkan antara al-maslahah dengan al-maqashid al-syar’iyyah (tujuan-tujuan hukum), yang pada hakekatnya sama dengan pengertian tersebut.
Pengertian-pengertian sebagaimana telah disebutkan diatas merupakan batasan yang diberikan oleh para pakar hukum Islam klasik, Sedangkan pakar-pakar hukum Islam belakangan (kontemporer), sepertinya mencukupkan definisi-definisi tersebut di atas. Artinya mereka menganggap cukup untuk merujuk pada pendapat Al-Ghazali, Al-Khawaritsmi, Al-Thufi dan lain-lainnya. Beberapa definisi tentang maslahat dengan rumusan yang berbeda di atas dapat dipahami adanya persamaan persepsi antara pakar hukum Islam yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa teori maslahat dalam pengertian syari’at adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat, karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan syari’at dalam menetapkan hukum. Kemaslahatan tersebut tidak hanya terbatas di dunia saja, melainkan kemaslahatan yang berkelanjutan di akhirat. Kata lain dari pengertian ini adalah, mereka mengkaitkan kemaslahatan dengan tujuan syari’at, dan sepakat bahwa pengertian kemaslahatan tidak hanya terbatas meraih manfaat saja, melainkan juga menghindarkan bahaya dan kerusakan.
B. Klasifikasi Maslahat
Berkaitan dengan upaya mengangkat teori maslahat sebagai pisau analisis dalam kajian hukum yang sah dan otoritatif, para pakar hukum Islam (ahli Ushul Fiqh) membagi atau mengklasifikasikan maslahat menjadi tiga katagori. Yaitu: mashlahah mu’tabarah (valid/populer), mashlahah mulghah (invalid/tidak legitimet), dan mashlahah mursalah (terbuka dan legitimet sebagai sumber hukum Islam). Pertama, Mashlahah mu’tabarah yaitu maslahat yang secara langsung terdapat pada sumber hukum Islam aslinya. Baik berupa al-Qur’an maupun al-Hadits. Oleh karena itu ia memiliki tingkat validitas yang paling tinggi keberadaannya dalam pandangan Syari’ (Pembuat hukum[23]), karena secara langsung ia telah mendapatkan legitimasi dari al-Qur’an atau al-Hadits. Contoh mashlahah mu’tabarah ini adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah, 275:
"Alladzina ya’kuluna al-riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathuhu al-syaithanu min al-massi zalika bi annahum qalu innama al-bai’u mitslu al-riba wa ahalla Allahu al-bai’a wa harrama al-riba, fa man jaahu mau'idhtun min Rabbihi fa intaha fa lahu ma salafa wa amruhu ilallahi, wa man 'adahu fa ulaika ashab al-nar, hum fiha khalidun "[24]
Artinya:
“Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Pdahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),.Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”
Halalnya berjual beli secara jelas telah ditentukan oleh ayat tersebut. Begitu pula haramnya riba. Hikmah dari maslahat yang ditimbulkan dari jual beli yang halal serta larangan riba tersebut adalah dalam rangka menjaga dan mengembangkan harta secara proporsional. Kedua, mashlahah mulghah adalah maslahat yang dianggap bertentangan dengan syari’at. Oleh karenanya keberadaan maslahat mulghah (sia-sia) ini baik secara esensial maupan subtansial dianggap invalid dan tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum. Contohnya adalah pengembangan harta atau uang secara ribawi seperti dalam perbankan konvensional. Sekalipun dengan alasan bahwa secara internasional konsep perbankan telah dikemas sedemikian rupa, sedangkan hampir seluruh umat Islam tidak dapat melepaskan diri dari jasa perbankan tersebut. Oleh karena itu dengan memandang maslahat agar keuangan umat Islam tetap berputar dikalangan umat Islam sendiri, di mana hasilnya dapat disalurkan atau digunakan untuk dakwah Islamiyah, maka didirikanlah perbankan dengan menggunakan simbul Islam sekalipun konsepnya tetap menggunakan kosep perbankan konvensional (riba). Pendirian bank semacam ini, sekalipun alasannya ingin mengembangkan dan menjaga harta serta niatan menegakkan agama (Islam), tetapi tetap saja secara operasionalnya bertantangan dengan ayat al-Qur’an di atas. Oleh karena itu pemaksaan terhadap penerapan teori maslahat jenis ini (mulghah), sekalipun secara formalitas menunjukkan adanya prestasi, akan tetapi secara esensial justru akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu sendiri. Ketiga, mashlahah mursalah, adalah maslahat yang posisinya berada antara mashlalahah mu’tabarah dan mashlalah mulghah. Yaitu suatu maslahat sebagai produk atau hasil pemikiran aktual yang secara yuridis tidak diperintahkan oleh al-Qur’an atau al-Hadits, tetapi juga tidak bertentangan dengan keduanya. Secara filosofis, maslahah mursalah berpotensi sebagai alat untuk pengembangan hukum baik dengan jalan merespon fenomena yang terjadi maupun berupa aktualisasi hukum-hukum yang telah ada untuk selanjutnya disesuakan dengan kebutuhan masa kini (kontekstualisasi hukum). Contohnya adalah pendirian bank sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pemilik modal dengan pekerja. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan. Akan tetapi tidak satu ayatpun dari al-Qur’an maupun al-Hadits yang melarang pendirian lembaga perbankan. Akad mudharabah (bagi hasil) yang dikenal selama ini, dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja. Di mana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Di samping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks hukum yang telah ada. Baik teks al-Qur’an maupun al-Hadits.
Secara otoritatif, mashlahah mursalah memiliki kekuatan sebagai sumber hukum dengan syarat bahwa suatu maslahat terkandung dalam maslahat dharuriyyat (primer), qhath’iyyat (pasti) dan kulliyat (menyeluruh).[25] Yang dimaksudkan dengan maslahat dharuriyat adalah maslahat yang sesuai dengan tujuan pokok hukum. Yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan maslahat qath’iyyat adalah maslahat yang terjadi dengan pasti tanpa diragukan lagi keberadaannya. Adapun maslahat kulliyat adalah suatu maslahat yang luas dan menyeluruh daya jangkauannya sesuai dengan ruang lingkup kebutuhan hidup dan kehidupan manusia tanpa memandang waktu dan tempat di mana hukum itu harus diwujudkan dan diterapkan.
Keseluruhan hukum (Islam) pada akhirnya akan mengarah pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut adalah menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akherat kelak. Pengertian maslahat dalam konteks seperti ini dartikan sebagai manfaat. Sedangkan manfaat dalam terminologgi hukum (umum) merupakan bagian dari tujuan hukum di samping keadilan dan kepastian. Sedangkan manfaat (maslahat) dalam terminologi hukum Islam harus selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan hukum esensial yang telah disepakati oleh ahli hukum. Tujuan-tujuan hukum esensial tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Kelima hal ini selanjutnya disebut dengan istilah kulliyat al-khomsah (pokok-pokok hukum yang lima).
Hubungan maslahat dengan tujuan hukum (maqasid syariah) adalah merupakan hubungan simbiosis. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Artinya, maslahat membutuhkan tujuan hukum (maqasid syariah), di sisi lain tujuan hukumpun juga membutuhkan adanya maslahat. Bertitik tolak dari pengertian ini, maka tidak semua maslahat dapat dipandang benar oleh hukum. Maslahat yang dibenarkan hanyalah maslahat yang merupakan pengembangan kulliyat al-khomsah (kelima pokok hukum) di atas. Untuk itulah dalam pengembangan kajian hukum (Islam) tidak boleh hanya terpaku pada teks-teks hukum secara lahiriyah (formalistic) saja. Penulusuran terhadap pengembangan hukum menjadi sangat penting. Sekalipun demikian penelusuran tersebut harus selalu berpijak dan bersandar pada teks-teks atau nas yang ada. Hal ini dilakukan demi untuk menjawab perkembangan dan perubahan sosial yang dalam kenyataannya melaju lebih cepat dari pada hukum itu sendiri.
C. Otoritas (Kehujjahan) Teori Maslahat
Untuk mewujudkan maqasid (tujuan pokok) syari’ah sebagaimana telah disebutkan, maka berdasarkan kekuatan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, maslahat dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu, mashlahah dharuriyyah (maslahat primer), mashlahah hajiyyah (maslahat sekunder) dan mashlahah tahsiniyyah (maslahat tersier).
Mashlahah Dharuriyyah (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan memelihara urusan pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, hal ini dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Kemungkinan terjadinya kekacauan tersebut menimpa sisi keagamaan atau keduniaan ataupun kedua-duanya sekaligus. Akibatnya mereka akan kehilangan keserasian dan kebahagiaan akhirat.
Sedangkan Mashlahah Hajiyyah (kemasalahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam memelihara al-maqashid al-syar’iyyah (tujuan syari’at/hukum). Jika tidak terpenuhi kemaslahatan tingkat ini, manusia akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keserasian dan kebahagiaan hidup[26].
Adapun Mashlahah Tahsiniyyah (kemaslahatan tersier), adalah bertujuan untuk memelihara kelima unsur al-maqashid al-syar’iyyah (tujuan syari’at/hukum) dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Apabila tidak tercapai kemaslahatan tingkat ini, manusia tidak sampai mengalami kesulitan, hanya saja ia tidak mencapai tarap hidup yang bermartabat atau terhormat.
D. Ruang lingkup Maslahat
Hubungan antara maslahat dengan tujuan hukum (maqasid syari’ah) sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah hubungan simbiosis[27]. Hal ini dimaksudkan agar dalam penjelajahan subyek terhadap obyek hukum dapat dengan mudah untuk diidentifikasi. Untuk itulah maslahat dikelompokkan menjadi tiga bagian[28], yaitu:
1. Al-mashlahah yang berkaitan dengan semua orang, seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid’ah[29] merupakan kemashlahatan yang berhubungan dengan semua orang, sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemadharatan (bahaya) bagi semua orang.
2. Al-mashlahah yang berkaitan dengan kepentingan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk menjadikan sebuah barang jadi atau setengah jadi, wajib menggantikan bahan baku yang dirusakkannya. Kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerima pesanan tidak hati-hati dalam pekerjaannya.
3. Al-mashlahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh[30] karena suaminya dinyatakan mafqud (hilang).
Mengenai pembahasan di atas, al-Thufi tidak sependapat dengan pendapat mayoritas pakar hukum Islam. Menurutnya pembagian al-mashlahah tersebut merupakan penyimpangan dan memberatkan saja, karena metode untuk mengetahui al-mashlahah lebih universal dan lebih mudah dari itu semua, mengingat Syari’(pembuat hukum) sangat memperhatikan kemaslahatan manusia.[31]
E. Dinamika Maslahat Sebagai Sumber hukum
Sebagai sumber hukum, maslahat tidak bersifat statis. Ia bergerak mengikuti irama kehidupan. Ditinjau dari konteks yang demikian ini, hukum itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.[32] Itulah sebabnya maslahat sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun[33] dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
1. Maslahat yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu, atau lingkungan , dan atau orang-orang yang menjalaninya. Hal ini terjadi hanya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu’amalah dan uruf (kebiasaan).
2. Maslahat yang tidak mengalami perubahan, bersifat tetap sampai akhir zaman. Kemaslahatan akan bersifat tetap walaupun waktu, lingkungan orang-orang yang berhadapan dengan kemaslahatan tersebut telah berubah. Kemaslahatan yang tidak berubah ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah[34].
Pembagian maslahat ke dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda ini, adalah hasil perenungan panjang oleh para pakar ushul fiqh (filsafat dan teori hukum Islam) sejak abad III-IV H., dan berlangsung hingga saat ini. Kesimpulan tersebut merupakan karya abstraksi intelektual yang luar biasa , dengan menggunakan metode ijtihad. Pembagian tersebut juga memberi rambu-rambu agar tidak seluruh maslahat yang muncul dalam benak setiap orang dengan begitu saja dapat dijadikan sebagai sumber atau pijakan hukum, yang pada akhirnya justru akan menyesatkan banyak orang. Maka dengan demikian diharapkan hukum selalu dapat menjawab tantangan yang selalu muncul sebagai isu global dalam kehidupan manusia.
[1]. Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan manusia dan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hal. 47
[2] Sebagaimana dibahas menurut terminologi sastra Arab, ungkapan (kalam) itu dibagi menjadi tiga macam. Pertama, ungkapan yang ringkas (kalam ijaz). Yaitu ungkapan atau penjelasan ringkas yang disampaikan baik melalui ucapan maupun tulisan. Ungkapan tersebut disampaikan secara ringkas dengan asumsi bahwa pembaca atau lawan bicara adalah orang yang cerdas dan mampu menganalisis ungkapan tersebut. Selain itu juga dimaksudkan dengan ringkasnya ungkapan tersebut diahrapkan dapat dianalisis dan dieksplorasi maknanya hingga memiliki jangkauan makna yang jauh lebih luas. Kedua, ungkapan panjang bermakna (kalam ithnab). Artinya ungkapan tersebut disampaikan (baik secara lisan ataupun tertulis) secara panjang lebar dalam rangka memberikan pemahaman yang baik kepada pendengar atau pembaca. Pembaca dianggap kurang begitu memahami apabila ungkapan tersebut hanya disampaikan secara global. Baca Ahmad al-Hasyimi, 1978, Jawahir al-Balaghoh fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi', Dar al-Fikr, hal. 32-44. Baca juga 'Alamuddin Muhammad Yasin bin 'Isa al-Fadani, 1992, , Rembang, Al-Ma'had al-Dini al-Anwar Sarang, hal. 84-89.
[3] . Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 10.
[4] Mudiarti Trisnaningsih, 2007, Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Bandung, CV. Utomo, hal. 124.
[5] Bellefroid dalam Kansil, CST, 1992, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, hal. 9
[6]Bandingkan dengan Sistem Hukum Amerika (Common Law System), meskipun keputusan pengadilan terdahulu dapat dipertimbangkan untuk keakuratan negara dalam Comman law, hakim berikutnya terikat, tetapi tidak oleh keputusannya itu, melainkan oleh prinsip-prinip yang secara eksplisit maupun implicit terkandung dalam putusan tersebut. Even where prior judicial decisions can be considered to state accurately the common law, a later judge is bound not by those decisions but by the principles implicit or explicit in them (cf. Postema 1945) dalam Roger Contterrell, The Politics of Jurisprudence: a Critical Introduction to Legal Philosophy, London, Butterworths, 1989, hal. 26 . Di sini teks keputusan hakim terdahulu lebih merupakan landasan atau rujukan di mana prinsip-prinsip hukum harus digali dan dicermati. Teks keputuan hakim terdahulu bukan merupakan sebuah teks yang begitu saja diambil untuk memutuskn sebuah perkara yang sedang dihadapi atau berlangsung.
[7] Alasannya sebagimana disebutkan dalam kitab Ushul Fiqh al-Islamy:
واما المعاملات فالعباد أدرى بمصالحهم، فكان لهم تحصيل هذه المصالح ، وإن خالفت نصوص الشارع
(Wa amma al-muamalatu fa al-ibadu adra bimashalihihim, fa kana lahum tahshilu hadzihi al-mashalih, wa in khalafat nushusha al-syari’)
Artinya:
“adapun pada bidang muamalat, para hamba (manusia) lebih mengerti akan kemaslahatannya sendiri, oleh karena itu mereka berhak menentukannya sendiri, sekalipun bertentangan dengan Syari’at (ketentuan Tuhan)”. Lihat Wahbah al-Zuaily, , 1986, Ushul al-Fiqh al-Islamy, juz 2, Damaskus, Dar al-Fikr, hal. 818
[8] Yang dimaksud dengan nas dhanny adalah nas yang memberikan peluang pemikiran manusia untuk ikut memikirkan pengembangan hukum berdasarkan nas yang tertulis (teks) dengan metode penalaran ilmiah (ijtihad). Itulah sebabnya ulama’ ushul mengartikan ayat-ayat yang mengandung hukum dhanny sebagai lafadh-lafadh yang dalam al-Qur’an mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk dita’wilkan. Misalnya lafadh musytarak (mengandung pengertian ganda, yaitu lafadh quru’ yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228) yang sekaligus memiliki makna suci dan haid. Selanjutnya baca Nasrun Haroen, 1997, Ushul Fiqh, Jakarta, Logos Waacana Ilmu, hal.33, dan Mahmud Saltut, 1966, Al-Islam Aqidah wa Syari’ah, Cetakan III, Dar al-Qalam, hal.516-519
[9] Sedangkan yang dimaksud dengan nas qath’y adalah nas yang memberikan kepastian hukum, sehingga tidak memberikan peluang kepada pemikiran manusia untuk pengembangan hukum melalui jalur penalaran (ijtihad). Maka dengan demikian ayat yang bersifat qath’y adalah lafadh yang mengandung pengertian tungal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Selanjutnya baca Nasrun Haroen, Ibid, hal. 32.
[10] Dasar hukum yang dijadikan alasan adalah sebagaimana berikut:
والمصلحة في تقدير الطوفي: هو بين النص الظني والمصلحة، أما النص القطعي فيمنع الطوفي تخالفه مع المصلحة، ولا تقدم المصلحة عليه حينئذ.
(Wa al-mashlahatu fi taqdiri al Thufy: huwa baina nash al-dzonny wa almashlahah, amma al-nash al-qath’iyyu fa yamna’u al-Thufy takhalufaahu ma’a al-mashlahah, wala tuqaddamu al-mshlahah alaihi hinaizin)
Artinya :
“Maslahat menurut pandangan al-Thufy, adalah antara nas yang dhanny dan maslahat, sedangkan antara nas yang qoth’y dengan maslahat al-Thufi mencegah adanya pertentangan. Pada waktu itu maslahat tidak boleh mendahului nas”. Lihat Wahbah al-Zuaily. Op.Cit. hal. 819
[11] Mahmud Syaltut, Op. Cit, hal. 345-346. Seperti dalam kasus delik sekual (zina), menurut Syaltut saksinya tidak harus empat orang laki-laki, bila secara material pembuktian itu telah kuat dan menunjukkan bukti-bukti yang sah, serta mashlahah menghendaki untuk itu. Padahal Al-Quran surat Al-Nur ayat 4 dengan jelas menyatakan:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera. Begitu juga menurut surat Al-Nisa’ ayat 15 yang berbunyi:
وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ .......الأية
Artinya: Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya).
[12] Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van hove, Jakarta, hal. 1038. Juga Al-Imam Abi Ishaq al-Syatibi, Al Muwafaqot, jilid 4, Dar al Kutub al Ilmiyyah, Beirut, hlm. 20-21, tth; mengemukakan bahwasanya ada lima tujuan yang paling mendasar sebagi alasan diturunkan syari’at Islam. Lima tujuan dasar itu, disebut dengan istilah al dloruriyyaah al khoms (lima kebutuhan pokok), yang diantaranya, Hifdzu al din (menjaga agama), Hifdzu al nasl (menjaga keturunan), Hifdzu al mal (menjaga harta), Hifdzu al aql (menjaga akal), Hifdzu al I’rdli (menjaga harga diri)
[13] Teori maslahat dalam pengertian ini sama dengan teori utilitarianisme oleh Bentham. Menurutnya, hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaran. Baca Lili Rasyidi, 2003, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung, Mandar Maju, hal. 116.
[14] Muhammad Taufiq, Al-Maslhah sebagai Sumber Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam “Istimbath” No.2, Vol. 2, Juni 2005.
[15] Izzu al-Din Abdu al-Salam, Qaawaid al Ahkam fi Mashalih al-Anam, jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, tth., hal. 5.
[16] Al-Syahrastani, 1967, Al-Milal wa al-Nihal, Mesir, Mustafa al-Baby al Halaby, hal. 199.
[17] Abd. Salam Arif, 2003, Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Hukum Mahmud Syaltut, Yogyakarta, Lesfi, hal. 3.
[18] Teks asli ayat tersebut adalah:
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ
[19] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, , tth, Al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul, jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, hal. 140
[20] Ibid, hal. 287
[21] Menurut al-Kawaritsmi sebagaimana dikutib oleh Wahbah dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islamy adalah:
"المراد بالمصلحة : المحافظة على مقصود الشارع بدفع المفاسد عن الخلق"
(Al-muradu bi al-mashlahah: al-muhafadhah ‘ala maqshudi al-Syari’ bi daf’I al-mafasid ‘an al-khalqi)
Artinya:
“Yang dimaksud dengan al-Mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”. Baca Wahbah al-Zuhaili, op. cit, hal. 757.
[22] Najm al-Din al-Thufi, Syarh al-Mukhtashar al-Raudlah, 1989, jilid III, Beirut, Muassasah al-Risalah, hal 239 .
[23] Menurut kajian hukum Islam yang dimaksudkan dengan Syari’ adalah Allah SWT dan Muhammad SAW sebagai utusanNya.
[24] Teks asli QS. Al-Baqarah 275 tersebut adalah:
šúïÏ%©!$# tbqè=à2ù'tƒ (#4qt/Ìh�9$# Ÿw tbqãBqà)tƒ žwÎ) $yJx. ãPqà)tƒ ”Ï%©!$# çmäܬ6y‚tFtƒ ß`»sÜø‹¤±9$# z`ÏB Äb§yJø9$# 4 y7Ï9ºsŒ öNßg¯Rr'Î/ (#þqä9$s% $yJ¯RÎ) ßìø‹t7ø9$# ã@÷WÏB (#4qt/Ìh�9$# 3 ¨@ymr&ur ª!$# yìø‹t7ø9$# tP§�ymur (#4qt/Ìh�9$# 4 `yJsù ¼çnuä!%y` ×psàÏãöqtB `ÏiB ¾ÏmÎn/§‘ 4‘ygtFR$$sù ¼ã&s#sù $tB y#n=y™ ÿ¼çnã�øBr&ur ’n<Î) «!$# ( ïÆtBur yŠ$tã y7Í´¯»s9'ré'sù Ü=»ysô¹r& Í‘$¨Z9$# ( öNèd $pkŽÏù šcrà$Î#»yz
#
[25]Chariri Ma’mun, Standar maslahat menurut Islam, http:/peinu-mesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/4.htm, diakses pada tanggal 15-22-2008
[26] Berdasrkan syariat Islam, dalam batas-batas tertentu kesulitan hidup itu dapat diatasi dengan rukhshah (dispensasi). Yaitu sebuah keringan terhadap kesulitan yang dihadapi atau dialami oleh manusia dalam persoalan ibadah maupun muamalah setelah diupayakan mencari jalan keluarnya, namun tidak juga menghasilkannya. Hal ini ditegaskan oleh kaidah hukum Islam yang menyatakan الضروراة تبيح المحظورات ((al-dharuraatu tubihu al-mahdzurat, kesulitan-kesulitan itu pada akhirnya mebolehkan sesuatu yang dilarang). Sudah barang tentu kebolehan melakukan larang di sini hanya sekedar menutupi kebutuhan primer, seperti dalam situasi terpaksa akad riba yang semestinya dilarang boleh dilakukan hanya sebatas untuk menutupi kebutuhan (primer) hidup saat itu saja.
[27] Pengertian hubungan simbiosis antara teori maslahat dengan tujuan hukum (maqashid syari'ah) di sini adalah: adanya saling membutuhkan antara keduanya. Teori maslahat akan bermakna (berfungsi) jika ia memiliki obyek atau fenomena hukum yang keberadaannya memerlukan nuansa baru atau perubahan. Di lain pihak tujuan hukum ingin merubah fenomena hukum tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana mereka berada pada waktu itu, sehingga dengan demikian tujuan hukum membutuhkan maslahat dan maslahatpun sebagai pisau analisis pembentukan hukum baru juga membutuhkan tujuan hukum, terkait dengan hukum aktual (baru) pada saat itu.
[28] Husain Hamid Hasan , 1971, Nadhariyyat al- Mashlahah fi al-Fiqh al-Islamy, Kairo, Dar l-Nahdhah al-Arabiyyaah, hal. 33
[29] Yang dimaksudkan dengan bid'ah di sini adalah segala persoalan baru dalam agama (ibadah) yang tidak ada dasar hukum baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits (tidak ada contoh dari perbuatan Rasulullah).
[30] Fasakh adalah istilah yang dipergunakan dalam ilmu fiqh untuk menyatakan rusaknya hukum pernikahan suami istri (bukan dengan jalan talak ataupun khulu’/talak tebus).
[31]Menurut al-Thufy, untuk mengetahui suatu kemaslaahatan hendaknya menggunakan kriteria sebagai berikut: pertama, Jika suatu perbuatan mengandung kemaslahatan semata, maka kerjakanlah; kedua, Jika suatu perbuatan itu mengandung mafsadah (kerusakan) semata, maka tinggalkanlah dan jangan dikerjakan; ketiga, Jika suatu perbuatan, disatu sisi mengandung kemaslahata dan di sisi lain ia juga menagndung mafsadah dengan kadar yang sama, maka tanyaknlah kepada ahlinya yang memiliki kemampuan untuk menentukan yang mana yang harus dilakukan atau dengan cara memilih sendiri antara keduanya. Contoh yang dikemukakannya adalah jika seseorang tidak menemukan cukup kain untuk menutup kedua kemaluanya, maka ia bisa memilih antara mendahulukan menutup qubul (kemaluan depan) atau duburnya (kemaluan belakang/pelepasan); empat, Jika suatu perbuatan disatu sisi mengandung kemaslahatan dan di sisi lain mengandung mafsadah dengan kadar yang berbeda, maka hendklah mentarjih (memilih) saalah satunya. Bila ternyata kemaslahatnnya lebih dominan, maka kemaslahatan yang harus didahulukan, tetapi jika sebaliknya, apabilaa mafsadah lebih besar dari pada kemaslahatan, maka meninggalkan mafsadah yang harus didahulukan. Oleh karena menjalankan dan mendahulukan yang lebih kuat merupakan tuntutan syara’ yang harus dilakukan. Komentar selanjutnya dari l-Thufi, apa yang telah dilakukan oleh para pakar hukum dalam pembagian al-mashlahah ke dalam beberapa bagian tersebut, semuanya telah tercakup daalam kaidah yang dikemukakannya di atas. Baca Najm al-Din al-Thufy, Op. Cit. hal. 214.
[32] Satjipto Rahardjo, 2007, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, hal. vii
[33] Nasroen Haroen, Op.Cit, hal.117.
[34] Ibadah yang dimaksudkan di sini adalah ibadah mahdhah (murni), yaitu ibadah yang secara jelas sudah diatur tata caranya oleh agama seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, sedangkan sebaliknya adalah ibadah ghoiri mahdhah (tidak murni) yaitu ibadah yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang dalam terminologi fikih Islam (Islamic Yurisprudent) disebut muamalah.
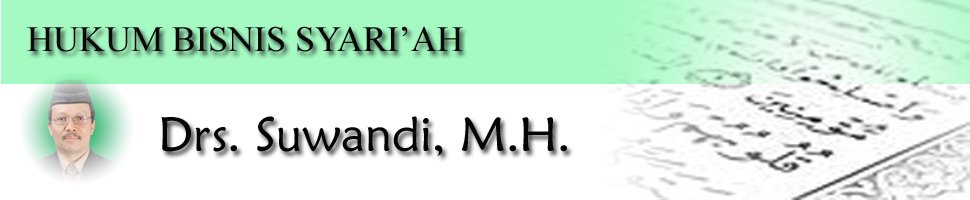


0 komentar:
Posting Komentar